Putri terbangun ketika malam telah bertengger di puncaknya.
Dinyalakannya lampu kamar. Pukul dua dini hari. Di luar sana, kesunyian telah
sempurna mengepung kota. Sayup-sayup terdengar suara tiang listrik dipukul
seseorang. Digelitiki rasa penasaran, Putri melangkah menuju ruang tamu.
Instingnya mengatakan ada kesibukan di sana. Tebakannya tak meleset. Dia
mendapati Bapak masih bergelut dengan pekerjaannya. Kertas-kertas berserak di
meja dan lantai. Ada bukit kecil di asbak, terbuat dari puntung-puntung rokok.
Tiga gelas kopi yang sudah kosong, beku di dekat Bapak.
Putri memandangi sosok lelaki yang hanya mengenakan kaos oblong
dan kain sarung itu. Dia tidak sadar kalau kacamatanya telah melorot ke hidung.
Wajahnya tegang. Sekali waktu, jemarinya meniti huruf demi huruf di depan
matanya. Begitu bersemangatnya dia, hingga tak sempat menyadari bahwa ketukan
yang ditimbulkannya telah melahirkan nada yang tersendat-sendat, yang hampir
tiap malam merusak kenyamanan tidur anaknya. Sekejap kemudian, dia menghentikan
ketikannya. Diam mematung, tapi pikirannya seperti meraba dalam kegelapan.
Mengetik lagi. Melamun lagi. Begitu terus-menerus. Ah, Bapak, desis Putri dalam
hati.
Mesin tik tua itu sangat berharga bagi Bapak. Suatu hari,
beliau pernah berkata bahwa dia lebih mencintai mesin tik itu ketimbang dirinya
sendiri. Pendapat yang berlebihan, menurut Putri. Tapi, kalau sudah melihat
bagaimana Bapak memperlakukan mesin tik itu, Putri benar-benar trenyuh. Inilah
jalinan cinta terunik yang pernah dilihatnya. Sejujurnya, Putri sudah jenuh
mendengar sejarah mesin tik itu. Sudah berkali-kali Bapak mengulangnya. Benda
itu dibelinya dengan harga miring di pasar loak. Manakala kisahnya sampai pada
asal-muasal uang untuk membeli mesin tik itu, makin berbinarlah mimiknya. Ya,
ya, Putri sudah hafal luar kepala. Dari hasil menyisihkan honor tulisan,
akhirnya dia bisa memiliki mesin tik yang lama menggoda dalam mimpinya.
Begitulah. Mungkin usia mesin tik itu jauh lebih tua dari
Putri yang kini duduk di bangku sekolah menengah umum. Setiap melihat mesin tik
itu, Putri seperti melihat sosok seorang pensiunan tua. Di sisa hidupnya, tidak
semestinya dia masih bekerja membantu Bapak menghasilkan tulisan-tulisan.
Gudang adalah tempat yang nyaman untuk benda antik itu.
Tapi tidak. Bapak sungguh telaten merawat mesin tik itu.
Sejarah, mungkin, membuat cinta Bapak tak pernah layu. Sudah beberapa kali
Bapak mereparasi kekasihnya itu. Tahun-tahun belakangan ini, dia mulai rewel.
Ada saja kerusakan yang terjadi, seperti pita yang kerap lepas dari tempatnya
atau huruf yang tercetak miring. Tapi, Bapak sabar meladeninya. Jika dia merasa
sanggup memperbaiki kerusakan itu, pasti dikerjakannya sendiri. Kalau dia
menyerah, dia tidak sungkan membawanya ke tempat servis.
*****
Akhirnya, bayangan yang Putri takutkan itu menjadi
kenyataan. Guru-guru di sekolah membuktikan ancamannya. Mulai hari ini mereka
menggelar aksi mogok mengajar sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini
benar-benar sebuah mimpi buruk. Bagaimana tidak, semua guru di kotanya, bahkan
di kota-kota lainnya, serempak melakukan aksi serupa. Mereka bersikeras agar
pemerintah pusat merealisasikan tuntutan mereka. Ah, begitu banyak cara
menyikapi suatu persoalan. Inilah pilihan terbaik di antara yang terburuk.
Seumpama macan yang terusik tidurnya, guru-guru di sekolah
Putri menggeliat dari kepasrahan yang lama melilit mereka. Mulai hari ini,
hampir seluruh sekolah di negeri Putri lumpuh total. Tidak ada kegiatan belajar
mengajar. Guru-guru mogok massal. Sejak pagi hingga siang hari, orang-orang
dipaksa menyaksikan pemandangan yang entah heroik atau menyedihkan itu.
Guru-guru dengan pakaian korps lengkap, berbondong-bondong menuju gedung wakil
rakyat. Mereka ingin menyampaikan aspirasi di sana . Mereka masih sempat
tersenyum dan memekikkan yel-yel, tapi sesungguhnya air mata menetes dalam
batin mereka.
*****
Sudah hari keempat Putri dan teman-temannya terlantar.
Beberapa guru memang tampak hadir di sekolah, tapi mereka tetap enggan memberi
pelajaran. Mereka hanya duduk-duduk di ruang guru. Berbincang dengan raut muka
tegang. Mereka tetap berkeras agar pemerintah segera membayar rapel gaji mereka
yang terus-menerus ditunda. Murid-murid bingung. Kalau begini jadinya, pihak
mana yang harus disalahkan?
"Teman-teman, sudah beberapa hari ini kelas kita
melompong tanpa guru. Rasanya hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kita
harus melakukan sesuatu."
"Tapi, tindakan apa yang bisa kita lakukan?"
"Saya yakin kita semua sudah mengerti masalah apa yang
menimpa guru kita, bukan?"
Sebagian dari mereka mengangguk mengiyakan.
"Kita semua tahu, menekuni profesi sebagai pendidik di
negeri ini begitu dilematis. Tidak usahlah saya jelaskan panjang lebar. Ini
sudah jadi rahasia umum. Apalah artinya gaji guru dibanding kebutuhan hidup
mereka? Belum lagi potongan di sana-sini. Kalau dulu, kita menganggap guru
adalah pekerjaan yang luhur dan mulia, tapi sekarang, kita telah melihat
kenyataan bahwa guru tak jauh beda dengan sapi perah."
Rapat terus bergulir. Ketika jam istirahat tiba, seisi kelas
membentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka berunding mencari jalan keluar.
Ternyata membahas apa yang bisa mereka lakukan sebagai bentuk solidaritas murid
kepada guru bukanlah masalah yang mudah.
Dari sekian banyak usulan, semuanya mengerucut pada satu
kesimpulan. Anak-anak itu bermaksud menyumbangkan uang kas kelas pada guru
mereka. Sejumlah uang itu tentulah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup
seorang guru. Tapi masalahnya, dari sekian banyak guru di sekolah itu, siapakah
yang lebih berhak menerima pemberian itu?
*****
Sejak perceraian yang menyakitkan itu terjadi, Bapak
memuntahkan esedihannya lewat tulisan. Dia seperti kesurupan kalau sudah di
depan mesin tik. Jemarinya melompat-lompat begitu liar, seliar ide dan
imajinasi yang ada di benaknya. Dia benar-benar produktif berkarya. Putri
memutuskan ikut Bapak. Biarlah dua adiknya yang masih kecil ikut Ibu. Putri
ingin belajar pada Bapak bagaimana menghayati hidup dengan sederhana dan
bersahaja. Diam-diam, Putri pun bercita-cita ingin seperti Bapaknya.
*****
Angin menabuh daun-daun. Terik matahari begitu menyengat.
Debu-debu beterbangan dibawa angin. Musim kemarau seakan enggan bersahabat pada
manusia di muka bumi.
Dari balik bingkai jendela, Putri memandangi daun-daun yang
menguning dan berguguran di halaman rumahnya, dihalau angin kemarau. Putri
mendesah gamang. Aduhai, lihatlah daun-daun itu. Seburuk apa pun mereka
diperlakukan cuaca, mereka akan kembali menjadi humus yang menyuburkan. Tapi,
kenapa kadangkala hidup tak sesuai dengan apa yang diharapkan?
Putri hanya mengurung diri dalam kamar ketika Bapak sedang
meladeni beberapa tamunya. Sayup-sayup didengarnya percakapan antara Bapak
dengan mereka. Hati gadis belia itu seperti disayat-sayat.
"Pak Sukri, kami harap Bapak berkenan menerima
pemberian kami ini, sebagai rasa simpati kami semua terhadap perjuangan
Bapak."
"Kami mohon Bapak tidak berkecil hati. Tidak ada maksud
kami melecehkan profesi Bapak. Kami tahu Bapak adalah guru dengan idealisme
tinggi. Kami juga tahu, kami tidak akan pernah bisa membalas jasa Bapak. Hanya
ini yang bisa kami berikan sebagai tanda terima kasih kami."
Sungguh, ingin rasanya Putri menjerit sekuatnya. Tapi sebisa
mungkin dia tahan. Putri tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan ini. Putri
ingin lari sejauh mungkin. Lari dari kepedihan yang menghimpit jiwanya. Ah,
hidup memang kejam. Sesengit apa pun meladeninya, tetap saja mereka terpojok. "Tuhan,
seperti apakah posisi kami di hadapanMu sesungguhnya?" gugat Putri dalam
hati.
*****
Putri terbangun ketika malam telah bertengger di puncaknya.
Dinyalakannya lampu kamar. Pukul dua dini hari. Dia merasa matanya sembab dan
bengkak. Rupanya sejak sore tadi dia tertidur beralaskan bantal yang basah oleh
airmata. Di luar sana, kesunyian telah sempurna mengepung kota. Sayup-sayup
terdengar suara tiang listrik dipukul seseorang. Digelitiki rasa penasaran,
Putri melangkah menuju ruang tamu. Tebakannya tak meleset. Dia mendapati Bapak
masih berkutat menyelesaikan pekerjaannya. Kertas-kertas berserak di meja dan
lantai. Ada bukit kecil di asbak, terbuat dari puntung-puntung rokok. Tiga
gelas kopi yang sudah kosong membeku di dekat Bapak.
Tiba-tiba suara mesin tik berhenti. Menyadari ada yang
sedang memperhatikannya, Bapak melirik Putri yang berdiri di dekatnya. Dari
balik kaca mata tebal itu, Putri masih dapat melihat jendela hati Bapak yang
kuyu. Mungkin, dia sedang sebisa mungkin menahan rasa sedih dan kecewa. Ah,
betapa ketabahanku tidak ada apa-apanya dibandingkan ketabahan Bapak. Putri
mendesah samar.
Dengan suara tersendat-sendat seperti caranya mengetik,
Bapak menceritakan kedatangan teman-teman Putri sore tadi. Putri benar-benar
bingung. Mulutnya serasa terkunci.
"Kamu masih percaya bahwa guru adalah pahlawan tanpa
tanda jasa, Putri?" tanya Bapak di penghujung ceritanya. Suaranya berat
dan gamang. Pertanyaan itu membuat Putri terkejut. Dia tidak menyangka Bapak
akan bertanya seperti itu. Ragu-ragu ditatapnya Bapak. Tapi Bapak malah balik
menatap Putri dengan mimik menunggu. Putri hafal tatapan itu. Tatapan seorang
guru yang menunggu jawaban dari muridnya. Putri gugup, menelan ludah seperti
menelan sebutir paku. Pak Guru Sukri masih menunggu jawaban dari muridnya.
Puti diam. Pak Sukri pun diam. Detik-detik berlalu dalam
kebisuan. Tak ada angin berembus. Sunyi menciptakan jarak yang terasa panjang
dan menyakitkan.
"Mulai detik ini, belajarlah untuk melupakannya,
anakku. Itu cuma omong kosong," pinta Pak Sukri pelan, lebih kepada
dirinya sendiri. Suaranya terasa getir dan parau. Sangat parau.
















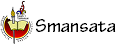


0 komentar:
Posting Komentar